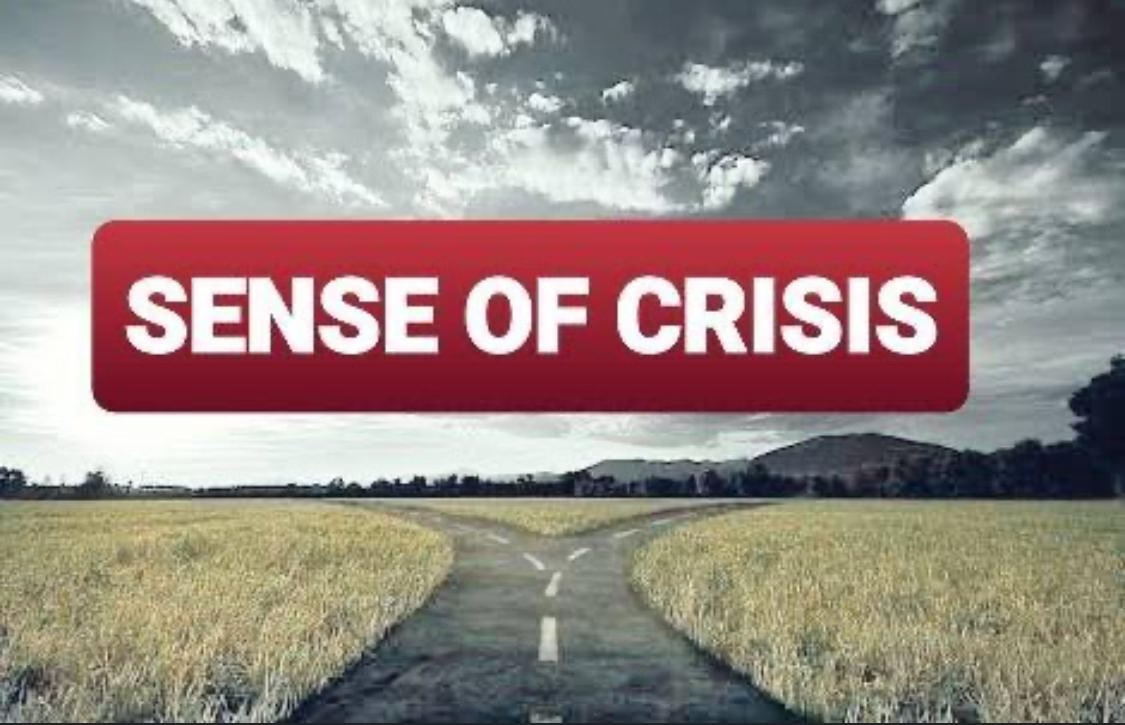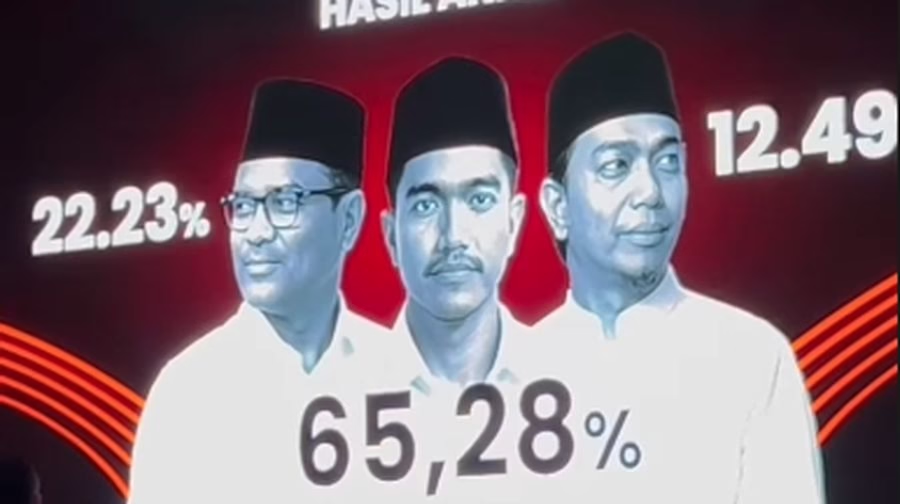kabarkita.net – Diawali dengan tarian, berakhir dengan bunga duka. Setidaknya begitulah gambaran dari kondisi terakhir di ibukota dan telah menjalar ke beberapa kota lainnya di Indonesia.
Jika ditarik ke awal, mungkin permasalahannya sederhana. Dimulai dengan kurangnya sense of crisis dari pihak-pihak yang seharusnya memilikinya dengan banyak. Dan kejadian beberapa hari terakhir membuktikan betapa kurang atau tidak adanya sense of crisis itu bisa berujung kepada peristiwa-peristiwa yang lebih besar.
Kurangnya sense of crisis dari PM Najib beserta istrinya berujung kepada kekalahan Barisan Nasional untuk pertama kalinya di Malaysia.
Kurangnya sense of crisis dari Presiden Soekarno terhadap pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pertama di malam 30 September 1965, membawa kepada akhir dari Orde Lama dan lahirnya Orde Baru.
Kurangnya sense of crisis Tsar Nicholas II terhadap penembakan terhadap demonstran di luar istananya, mengakhiri ratusan tahun perjalanan Tsar di Rusia.
Lalu sefatal apa kekeliruan dalam memahami sense of crisis ini ? Sebagai perbandingan, jika di zaman Tsar Russia saja bisa mengakhiri perjalanan kekaisaran Russia yang sudah berabad-abad, bayangkan apa yang bisa terjadi di zaman media sosial seperti sekarang ini.
Video berjoget di DPR RI, berujung kepada demonstrasi, jatuhnya korban pengemudi ojek online di Jakarta, dan terakhir pembakaran gedung DPRD di kota-kota besar Indonesia, yang juga sudah memakan korban jiwa.
Dan bahkan kita belum berbicara mengenai hidden agenda yang sangat berkemungkinan disisipkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang menginginkan chaos terjadi dimana-mana, berjilid-jilid, yang berujung kepada suksesi kah, deletigimasi kah, atau lebih jauh revolusi. Starting point? Sense of Crisis.
Sebagai aparatur negara baik itu di eksekutif ataupun legislatif, terlalu nyaman itu berbahaya. Karena bisa membuat lupa anda bekerja untuk siapa. Membuat anda lupa bahwa ada ratusan juta orang yang harus diperjuangkan nasibnya, kesejahteraannya dan dilindungi kemerdekaannya. Termasuk kemerdekaannya untuk menyampaikan pendapat, kritik atau saran.
Klise ? Bukan. Itu fakta sekaligus filosofinya. Tetapi banyak yang terlupa, karena filsafat kalah tampil di fyp media sosial dibandingkan produk terbaru dari brand fashion, atau gaya hidup hedon.
Sehingga tidak salah yang merasa punya jas paling mahal, sepatu paling trendi, jam paling langka, menjadi orang yang merasa paling harus didengar, dilayani dan paling benar.
Kembalikan saja fungsi aparatur negara sesuai dengan filosofinya. Pelayan publik. Tidak peduli seberapa tinggi pangkat dan jabatannya. Berikan mereka fasilitas yang cukup untuk menjalankan perannya, dan tidak perlu berlebihan. Jika mereka menolak, yakinlah masih banyak rakyat Indonesia yang memilih hidup cukup dan bisa berperan bagi kemaslahatan umat.
Toh dulu para pejabat tinggi juga tidak hidup mewah. Toh Republik tetap berjalan bahkan bertaring. Bukan berarti para pejabat itu juga harus melarat, namun tidak perlu berlebihan. Terlebih jika disparitas di kalangan masyarakat masih tinggi.
PM Singapura salah satu pejabat yang mendapatkan gaji yang paling tinggi. Tetapi tidak ada yang komplain karena mayoritas ekonomi rakyatnya juga bagus. Begitu juga di beberapa negara lain. Intinya people first.
Namun yang tidak kalah pentingnya, tetap waras dan masuk akal dalam beraksi ataupun bereaksi. Satu statement keliru dari seseorang, tidak berarti kita memiliki hak untuk membongkar rumahnya. Karena walau bagaimana pun kita bangsa yang terkenal dengan adab. Dan sebuah pilihan yang tidak baik untuk menghilangkan identitas itu, walaupun di tengah lingkungan yang terkadang memaksa.
Apalagi jika aspirasi tidak lagi murni dan ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu. Sudah saatnya kita semua kembali ke filosofi kita berbangsa dan bernegara. Mereka mungkin keterlaluan, tapi bukan berarti kita harus membakar habis bangsa dan rumah sendiri.
Penulis: NN